Juni
Aku menekuri ujung sepatu yang kupakai. Sialnya, sepatu ini kembali melempar ingatanku pada wajah gadis itu. Katanya, dulu, ia paling senang melihatku memakai sepatu ini. Perutku mual, aku mengalihkan pandanganku menuju hamparan parkiran pesawat terbang di sisi seberang jendela kaca yang tebal. Hujan jatuh satu-satu menepuk landasan yang berkilau. Aku membuang napas perlahan, mencoba menyusun kembali pikiran waras yang belakangan entah hilang ke mana.
Kulirik jam yang melingkar di tanganku. Seharusnya, sejak sejam yang lalu pesawat yang kutumpangi sudah berangkat. Sialnya, entah kenapa, pesawat dengan logo singa merah itu benar-benar sepakat untuk membuatku semakin jengkel hari ini. Melalui pengeras suara, seorang perempuan mengumumkan bahwa pesawat yang kutumpangi harus diundur jadwalnya sekitar tiga jam karena kesalahan teknis. Suara mendayu yang ia kumandangkan, beserta sebotol air mineral dan roti manis yang disuguhkan oleh pegawai maskapai sebagai permintaan maaf, tidak sungguh-sungguh membuatku tenang. Aku semakin mual. Kupijat sisi kiri dan kanan pelipisku. Sambil memejamkan mata, bayangan perempuan itu semakin utuh menggantung di ingatanku.
Perkenalan kami adalah skenario Tuhan yang paling lucu. Saat itu, aku tengah menuruni jalur pendakian Ciwidey di pagi yang amat buta, bersama teman-teman kantorku. Kami turun dengan tawa yang meledak-ledak. Kali ini, agenda mendaki disponsori oleh perayaan putus cinta salah satu teman kantorku, Bayu. Tepat hari di mana ia ingin melamar pacarnya, hari itu pula ia diputuskan, karena pacarnya mengaku hamil oleh rekan kerjanya.
“Perempuan sialan. Aku sudah menjadi pacarnya lima tahun. Lima tahun, bisa kalian bayangkan itu? Sia-sia. Dia ternyata lebih memilih lari ke dalam pelukan lelaki lain!” Bayu mengumpat semalaman. Sembari menjerang air panas untuk membuat kopi, ia menangis. Lalu tertawa lagi. Kemudian menangis tersedu-sedu. Aku dan kedua kawanku lainnya hanya bisa diam dam membiarkan Bayu meluapkan emosinya.
Pukul dua pagi, Bayu memutuskan untuk berteriak kencang di tengah kegelapan malam. Ia mengaku lega. Kawanku Danar, lekas masuk ke dalam tenda dan mengambil sesuatu dari ranselnya.
“Hadiah buat kamu, Yu!” Ia melempar sebuah buku ke arah Bayu. Bayu menangkapnya dan menyoroti sampul buku dengan senter kepala yang ia kenakan. Buku berupa kitab kamasutra, tips agar ia jago di ranjang.
“Kalian memang asu!” Bayu melempar buku ke arah kami lalu terbahak-bahak.
***
Aku selalu bilang, aku tidak percaya pernikahan. Bahkan, aku merasa aku akan baik-baik saja hidup sendiri hingga tua nanti. Aku ingin menabung, lalu membeli sebuah hunian di pedalaman, memelihara dua atau tiga ekor anjing, dan bercocok tanam di sana. Semuanya terasa baik-baik saja. Sempurna.
Sampai akhirnya aku bertemu perempuan itu.
***
“Mas! Mas! Dalamannya jatuh!” Suara perempuan itu menggema. Aku dan teman-temanku menoleh ke belakang.
Di sana pertama kali aku bertemu dengannya. Perempuan semampai dengan rambut ombak sebahu, menggendong ransel besar dan memegang tongkat kayu panjang di tangan kanannya. Di tangan kirinya, sebuah pouch transparan bening berisi beberapa potong pakaian dalam pria terlihat jelas. Aku panik. Itu milikku. Aku langsung berbalik melihat ranselku. Bagian bawahnya terbuka! Sialan. Aku buru-buru setengah berlari menuju perempuan yang dengan santainya melambai-lambaikan pouch ke arah kami. Semua teman-temanku tak bisa menahan tawa mereka. Wajahku merah padam. Cepat-cepat kuambil pouch milikku dari perempuan itu.
“Tasnya terbuka, Mas. Diperbaiki dulu!” Ia berkata sambil memamerkan senyumnya yang lebar. Rambut berombaknya bergerak-gerak lucu. Ia hanya sendirian, ikut menyusuri jalur penurunan. Aku menatapnya sekilas. Ia tengah menggaruk-garuk alis tebalnya dengan ujung telunjuk.
“Terima kasih, ya!” Aku menjawab singkat dan berbalik cepat-cepat. Teman-temanku masih tertawa. Kami menyusuri penurunan dengan suara tawa mereka yang sepertinya tidak akan habis.
Perempuan itu masih di belakang. Berjalan pelan sembari membunyi-bunyikan tongkat kayunya di tanah. Aku berbalik beberapa kali. Ia berhenti beberapa kali untuk memotret dari kamera saku, sembari mengunyah dedaunan merah yang kuyakin itu adalah tanaman begonia.
Perempuan aneh. Sesekali, ia menyanyikan lagu-lagu yang aku tak kenali. Bahkan, ia sempat berteriak beberapa kali dan berhasil membuat kami berbalik, menyangka ia terjatuh, dan ia hanya tertawa lebar dan berkata ia sedang ingin berteriak kencang. Perempuan aneh. Sangat aneh.
Sampai di bawah, aku langsung melesat menuju antrian toilet umum. Teman-temanku sudah duduk rapi di warung kopi dan mengunyah berbagai gorengan di sana. Aku butuh menyikat gigiku dulu.
Kulirik sekilas, perempuan itu juga duduk di sana. Ia sedang melahap mie rebus. Tak lama, ia sibuk dengan telepon genggamnya sembari terus menggaruk alisnya.
Setelah selesai dengan urusan kamar mandi, aku ikut berbaur dengan teman-temanku. Alif, temanku yang paling tengil, menjawil lenganku sambil menunjuk perempuan itu dengan dagunya.
“Apaan?” Tanyaku risih.
“Kupanggil gabung ke sini, ya?” Tanya Alif.
“Terserah!” Aku menjawab ketus, masih teringat insiden pakaian dalamku yang jatuh tadi.
Tak butuh persetujuanku, Alif sudah melesat ke meja tempat perempuan itu duduk. Entah ia berbincang apa, akhirnya perempuan itu berjalan menuju meja kami duduk.
Ia duduk di hadapanku. Sambil terus tersenyum. Kemudian, ia mengambil topi rimbanya dari saku celana yang lebar, menepuknya, lalu menyisir rambut berombaknya dengan jemari, dan mengenakan topi di atas kepalanya.
“Ah, hei, namaku Juni.” Ia mengenalkan diri sembari menawarkan jabat tangan dengan kami semua. Teman-temanku memperkenalkan diri dengan semangat, tak terkecuali Bayu yang baru saja patah hati. Tiba giliranku.
“Aku Rama.”
“Yang tadi pakaian dalamnya kau temukan, Juni!” Danar membalas tengil. Kutatap tajam Danar dengan ujung mataku.
“Ohaha. Kalau di dongeng-dongeng, tuh, yang ngambil baju bidadari yang lagi mandi kan akhirnya nikah sama bidadarinya, haha.” Juni menjawab ringan. Ia tertawa dengan leluconnya sendiri.
“Hei, haha, apakah kau menganggap Rama adalah bidadari yang kehilangan pakaian dalam? Haha!” Alif tertawa lebar sambil menepuk-nepuk pahanya sendiri. Aku? Diam dan mengutuk semua teman-temanku dalam hati. Soal perempuan ini? Perempuan aneh.
Entah bagaimana, akhirnya Juni ikut menumpang di mobilku setelah diyakinkan oleh Danar. Kami semua akan kembali ke Jakarta. Perjalanan enam jam yang kuharap tidak akan jadi perjalanan olok-olokku, terjadi juga. Alif menawarkan diri menyetir. Dan entah bagaimana, aku duduk bersama Juni di kursi tengah, karena Alif memilih mengkudeta kursi belakang bersama semua tumpukan tas kami.
Perjalanan yang kuharap tidak pernah terjadi.
Perkenalan yang kuharap tidak pernah kualami.
Sebab saat itu, aku dikutuk perkataanku sendiri. Aku jatuh cinta!
***
Setelah bercerita banyak hal selama perjalanan Ciwidey Jakarta, aku cukup banyak tahu soal Juni. Ia perantau dari salah satu kota di bagian timur Indonesia. Ia bekerja sebagai staf editor di salah satu agensi ternama di Jakarta. Dan lebih anehnya, ia sering bepergian mendaki seorang diri berhari-hari.
“Tak takut?” Aku bertanya.
“Takut apa? Ah, aku takut ular sebenarnya, tapi belajar saja soal kontur tanah mana yang tak ditinggali mereka, semua akan aman,” ia menjawab ringan.
Betul-betul perempuan aneh.
Dari situ, kami lalu bertukar kontak. Saling menanyakan kabar. Dan di bulan berikutnya, Juni mengajakku menyaksikan konser musik yang diadakan kantornya. Tak sekali dua kali, ia yang selalu mengajakku duluan. Entah itu makan siang, pergi ke museum, nonton film, menyaksikan pameran, atau sekadar mencoba beberapa tempat makanan di beberapa titik halte di kota Jakarta.
***
Semakin mengenalnya, aku semakin menyukainya. Ah, lebih tepatnya tertarik. Namun, aku tak yakin Juni menunjukkan ketertarikan yang sama. Aku cukup diam. Menikmati hari-hari yang kami lalui sebagai “teman dekat.”
Teman-teman kantorku selalu menanyakan perihal hubunganku dengan Juni. Selalu kujawab kami masih berteman baik. Dan disambut ledekan satu dua dari mereka.
“Ga mau diseriusin aja tuh si Juni? Anaknya asyik, loh!” Sosor Alif. Ia memang paling semangat membahas topik per-Juni-an di antara kami. Tanyanya disambut tawa dan ledekan dari teman-temanku yang lain.
***
Namun semua hanya sampai di situ. Tak terasa, setahun sudah aku mengenal Juni. Sampai di satu hari, aku merasa yakin ingin menyatakan perasaanku kepada Juni. Hidup di sebuah rumah jauh dari hiruk pikuk kota bersama anjing-anjing, dan ditemani Juni, sepertinya akan terasa sangat sempurna.
Hari itu, aku mengajaknya mendaki. Kali ini ke tempat yang sama seperti pertemuan kami pertama kali, Ciwidey.
“Ah, Ram! Kebetulan banget aku pengin ngomong sesuatu juga. Kita naik Sabtu, ya, balik Minggu pagi. Malam aku mau pulang soalnya.” Katanya lewat telepon setelah kuajak.
“Pulang ke Sulawesi, Ju?” Tanyaku heran.
“Iya. Nanti aku cerita, ya!” Ia menjawab semangat seperti biasa. Aku menutup sambungan dan mencoba mengumpulkan keberanian.
***
Sabtu subuh, kami berangkat menuju Ciwidey. Naik ke puncak paling bawah. Menyaksikan matahari tenggelam sembari menyesap kopi hitam tanpa gula. Kesukaan Juni.
“Ju, aku pengin ngomong sesuatu.” Kataku membuka pembicaraan.
“Oia, apa itu, Ram? Aku juga pengin cerita nanti!” Katanya sambil tersenyum lebar. Barisan giginya yang rapi selalu berhasil mencuri degup jantungku.
“Kamu dulu, deh.” Kataku. Sebuah keputusan yang amat salah.
“Aku akan menikah, Ram. Selasa nanti acara lamaranku. Pengin banget kamu bisa datang juga!” Ia bercerita ringan. Telingaku berdengung. Canting kopi yang kupegang nyaris jatuh.
“Kau mau ngomong apa, Ram?” Dia menyentuh lenganku. Aku tersengat.
“Oh, ga, kok, cuma pengin cerita masalah kerjaan aja. Nothing important. Ehe.” Aku menjawab sekenanya. Malam itu, adalah malam paling buruk di puncak yang aku lalui. Aku tak bisa tidur. Langit bertabur seribu bintang yang selalu berhasil membuatku tersenyum, kali ini hanya membuatku sesak.
Keesokannya, kami turun dengan banyak diam. Kakiku lemas. Beberapa kali aku terantuk akar pohon dan Juni berusaha menangkapku yang nyaris terguling. Menuju Jakarta, Juni menawarkan diri untuk menyetir.
Itu kali terakhir aku melihatnya.
***
Akhirnya pesawatku lepas landas. Terbang menuju kota Juni. Ini sudah satu tahun lewat dari kejadian di Puncak Ciwidey. Sejak saat itu, aku tak pernah mengontak Juni. Beberapa kali Juni mencoba menghubungiku, selalu kusanggah. Ia juga bertanya pada teman-temanku, dan hanya mendapat jawaban sekenanya.
Aku sedang tidak baik-baik saja. Sudah dua tahun, namun aku masih mengutuk kebodohanku yang diam atas perasaan valid yang kurasakan terhadap Juni.
Pesawat mendarat dengan sempurna. Tiba di kota Juni, aku ditawari pemandangan laut yang luas. Langit sudah berwarna jingga pekat. Sudah hampir malam. Jemputan hotel sudah menantiku di pintu kedatangan.
Bukan. Aku bukan ke sini untuk menemui Juni. Aku ke sini karena diutus kantor untuk menyelesaikan beberapa urusan. Aku sudah menolak, namun perintah atasanku tidak bisa ditawar-tawar lagi.
Empat hari di kota Juni menyisakan sesak yang amat besar. Setiap kali aku diajak kolega untuk berkunjung ke beberapa titik di kota itu, semuanya menyisakan soal Juni. Ia sering bercerita tentang kota ini. Tentang lautnya yang cantik. Tentang makanan lautnya yang enak. Tentang keluarganya. Tentang sudut-sudut kota yang bisa tergambar jelas di kepalaku.
***
Empat hari. Aku tak tahan untuk tidak melakukan itu. Kutekan nomor telepon yang sudah sangat kuhapal di luar kepala. Aku mengirim pesan singkat.
“Aku sedang di kotamu. Satu jam lagi pesawatku lepas landas. Apa kabar?” Gawaiku dengan cekat mengirim pesan. Melesatkannya lewat pemancar. Dan mungkin sedang dibaca Juni yang sedang duduk menikmati kopi sore bersama suaminya.
***
Aku berdiri di luar bandara. Bandara kelas tiga di kota Juni tidak bergitu ramai. Aku sedang melihat-lihat gambar di sepanjang tembok bandara. Lukisan-lukisan. yang sepertinya bercerita tentang cerita rakyat di kota ini.
Sampai tiba-tiba bahuku ditepuk keras dari belakang. Aku terperanjat.
Juni.
Dia ada di hadapanku.
Juni.
Perempuan aneh berambut ombak yang masih saja sebahu.
Juni.
Tersenyum lebar dengan mata yang ikut tersenyum.
Napasnya tersengal. Ia hanya memakai kaos hitam berlengan panjang dengan celana piyama selutut, dan sepasang sandal jepit yang kusam. Sangat terlihat ia amat buru-buru dan berlari menuju ke tempatku. Tangannya menggenggam telepon genggam dan kunci motor. Aku ingat ia bercerita rumahnya hanya selemparan batu dari bandara kota ini.
Ia tersenyum lebar. Lalu tiba-tiba ia menangis. Bahunya berguncang.
“Hei, kamu kenapa?” Aku bertanya kaget. Beberapa orang memerhatikan kami. Aku menarik tangannya untuk duduk di deretan kursi panjang.
Ia berkeras. Balik menatapku tajam dan tiba-tiba satu tamparan keras melesat di pipiku. Panas.
“Kamu kenapa, Ju?” Aku bertanya kaget.
“Kamu yang kenapa? Kamu yang kenapa tiba-tiba lari dari jangkauanku? Kamu yang kenapa hanya diam saja, dan bahkan aku harus mengetahui isi perasaanmu dari Alif? Kamu yang kenapa tiba-tiba menghilang, pindah kontrakan, bahkan tidak pernah ada saat aku berkunjung ke kantormu? Kamu yang tiba-tiba kenapa mengganti semua kontakmu dan hilang seperti ditelan bumi, hah?” Juni merepet sambil menangis. Kutarik tangannya menuju kursi panjang yang kosong. Beberapa pasang mata makin memerhatikan kami.
“Juni, kamu baik-baik saja?” Ia tidak menjawab. Masih menangis. Matanya menatap sepatu yang kukenakan. Sepatu hadiah ulang tahun pemberiannya. Ia semakin menangis.
“Bagaimana pernikahanmu?” Aku bertanya tanpa aba-aba.
Ia tertawa. Sambil memainkan mainan kunci yang ada di tangannya.
“Menikah apanya? Aku tak jadi menikah. Aku tak bisa berdamai dengan perasaanku terhadapmu. Aku tak bisa meneruskan perjalananku setelah sampai di rumah setahun lalu, dan membaca pesan Alif yang masuk ke telepon genggamku. Syukurnya semua bisa mengerti. Lelaki yang dijodohkan denganku pun tak memaksa.,” ia merepet. Aku terkesiap.
“Aku tidak bisa berdamai dengan kau tiba-tiba menghilang, Ram. Aku memutuskan pindah pekerjaan. Tinggal jauh dari Jakarta. Aku terus mengutuk diriku yang berbicara duluan di puncak waktu itu. Aku, aku, aku tidak bisa berdamai dengan semuanya.” Kali ini tangisnya pecah. Aku menarik napas panjang. Kuputuskan menarik Juni ke dalam pelukanku. Membiarkan ia menangis di sana.
***
Suara pemberitahuan panggilan terakhir untuk penerbanganku tidak kuacuhkan. Aku memilih memeluk perempuan aneh ini di sini. Membiarkan ia menumpahkan semua emosinya. Tak lama, deru pesawat lepas landas terdengar. Aku, masih memeluknya.
Muara Beliti, 2020.
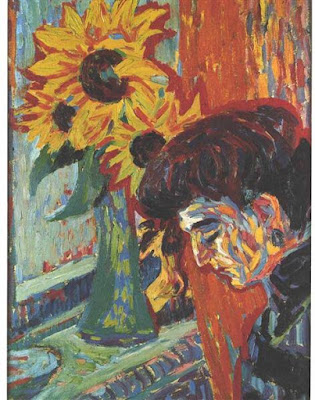


Comments
Post a Comment